
Dilema Bernama ‘Indie’, dan Prediksinya di Tahun 2018
Tantangan indie zaman sekarang lebih berat: quality minded. Bagaimana setiap musisi tetap mencipta dan memainkan musik sebaik dan sebagus mungkin.
Sejak Januari 2018, majalah musik ternama dan terakhir di Indonesia, Rolling Stone Indonesia (RSI) resmi tutup buku. RSI menyusul aneka media cetak lain yang sudah duluan collapse: HAI, Gitar Plus, Trax, Kort, dan Newsmusik. Label rekaman besar pun berguguran di Indonesia, bahkan yang juga franchise internasional macam Sony Music dan Warner Music.
Memasuki awal 2018 ini, pemusik Indonesia sudah berubah, tak sama lagi seperti 4-5 tahun lalu – di mana harus bergantung penuh ke label besar, masuk televisi/radio, baru merambah panggung-panggung. Bisa dibilang, sekarang semua pemusik Indonesia sejatinya sudah indie – independen dari segala hal. Apalagi didukung perangkat teknologi dan arus informasi digital yang memudahkan mereka untuk go public, tanpa harus melalui jenjang konvensional macam itu.
Bahkan musisi senior yang sudah jadi legenda, akhirnya menjadi indie kala merilis album barunya. Band rock 1990-an macam Kidnap juga God Bless yang merilis album baru, nyatanya sudah tidak memakai label besar lagi. Mereka memanfaatkan jejaring media sosial dalam mengumumkan aksi comeback-nya.
Bahkan penggunaan istilah ‘indie’ dan ‘non-indie’ diprediksi akan semakin rancu. Disinyalir, tak perlu lagi ada dikotomi baku yang memisahkan kedua esensi tersebut. Sebagaimana istilah ‘underground’ – yang di era 1990-an sampai 2000, yang seolah hanya berlaku kepada band beraliran rock atau metal saja, sedangkan hari ini, semua yang tidak over-exposured bisa turut dikategorikan underground (bahkan akun-akun sosmed pun banyak yang sudah ‘bawah tanah’).
Kini, semua pemusik rata-rata mampu memproduksi single dan albumnya secara mandiri, pun manajemen artisnya. Apa yang dimaksud "pasar musik" pun sudah tidak punya arti secara pasti. Faktanya, hampir semua area publik (yang menggunakan musik sebagai latar pengiring) toh ternyata masih bisa mengibarkan bisnisnya dengan memutar musik-musik yang tren di era 1960-2000. Belum lagi untuk pasar rilisan fisik seperti kaset, vinyl, dan CD, yang tempo hari sempat dianggap "kuno", ternyata sama sekali belum punah – dari peminatnya yang semakin muda.
Tantangan zaman sekarang lebih berat: quality minded. Bagaimana setiap musisi tetap mencipta dan memainkan musik sebaik dan sebagus mungkin. Untuk sektor promosi, kompetisi yang akan semakin marak di dunia indie adalah ‘perlombaan’ dalam ‘mengamankan’ posisi masing-masing, baik di panggung lokal maupun internasional.
Berarti, musik indie sedang di ambang tantangan besar. Kemudahan teknologi membuat anak-anak indie bisa “naik satu tingkat”. Mereka bisa dengan mudah menjalin kedekatan dengan banyak pendengar/konsumen. Di satu sisi, dengan ‘tumbang’-nya label dan majalah musik mapan, maka ‘populasi’ klan populer, akan otomatis turut serta menggunakan medsos dan teknologi juga dalam berkarir. Yang satu ‘naik kasta’, yang satu lagi ‘turun kasta’. Artinya, indie dan ‘major’ kini telah duduk di satu singgasana yang sama.
Hal yang saya khawatirkan adalah, anak-anak indie yang masih menganut paham ‘skill is dead’, akan ‘termakan’ oleh para mantan major culture yang kini memenuhi medsos. Kekhawatiran yang terlalu dini, memang. Tapi ini beralasan, mengingat nantinya label-label indie akan semakin ‘mahal’. Kekhawatiran ini masih sama dengan mereka-mereka yang masih mendebatkan “Apakah rock and roll sudah mati?”. Rasanya, jelas tidak.
Justru, yang akan terjadi sejak 2018 (dan tahun-tahun ke depannya) adalah perubahan esensi, bahwa “Rock and roll adalah milik semua khalayak”. Dalam arti lain, gejolak dan persaingan antar musisi akan semakin keras dan panas di media sosial – sebagaimana perusahaan iklan yang berbondong-bondong mulai meninggalkan televisi dan beralih ke YouTube, sejak penggunaan TV kabel rumahan (streaming TV providers) mulai terjangkau banyak khalayak.
Kesimpulannya, dunia indie akan semakin ‘rock and roll’. Akan sekeras batu, namun tetap harus bergulir. Akan semakin ‘rolling stone’. Mungkin iya, bila saya analogikan, bahwa nama ‘rolling stone’ telah mati sebagai majalah – namun dalam esensi yang lebih luas, nama itu justru sedang bertransformasi jadi lebih kontekstual – menjelma jadi zeitgeist (jiwa zaman) yang baru.
Sumber foto : Show Atanabe (Deviant Art)


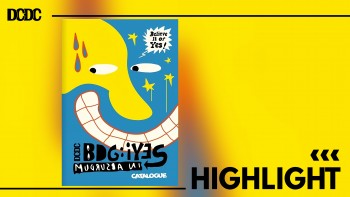












Comments (0)