
Ars Longa, Vita Brevis
“Art is long and life is short, and success is very far off,” tulis J. Conrad, yang dibahasakan The Kuda: “Pada anggur, puisi atau kebajikan yang anda inginkan. Gelombang, bintang, burung, jam akan menjawab anda.” Ok, baiklah, boleh dituang saja anggurnya, karena saya akan mulai mengoceh.
Oleh Rio Tantomo
Satu yang paling menyebalkan dari berada di barisan depan panggung The Kuda malam itu adalah pikiran kalau kacamata sialan ini sebaiknya dilepas saja; menghadapkan diri pada kenyataan mata kabur yang terus merengut dalam usaha melihat lebih jelas. Tapi hampir minus tiga, dan tidak ada yang bisa menjamin keselamatan seorang cacat netra ringan macam itu kecuali, tentu saja lensa-lensa cekungnya. Jadi saya memutuskan untuk tetap membiarkannya bertengger di atas hidung dan maju lebih dekat, karena terlalu bodoh rasanya kalau cuma berakhir diam di belakang tanpa ambil bagian ketika kerusuhan seperti ini sedang indah berlangsung.
 Sebelumnya, dari pinggir bar ketika termos berisi Merlot gelap, yang dalam hal ini tentu saja diselundupkan, terus disesap, saya telah melihatnya: riak terjangannya begitu deras dan keras di sana. Brutal. Saling timpa. Hantaman kepala dan sepatu terus beradu sembarangan selama musiknya menyala. Bahkan ketika berhenti pun tidak lantas mereda. Masih saja ada yang coba mendaki pundak-pundak punggung yang terbuka, mereka tengah bersenang-senang tanpa belas kasihan. Dan itu kasar, juga lapar setengah sadar. Liar, mungkin itu kata yang paling tepat.
Sebelumnya, dari pinggir bar ketika termos berisi Merlot gelap, yang dalam hal ini tentu saja diselundupkan, terus disesap, saya telah melihatnya: riak terjangannya begitu deras dan keras di sana. Brutal. Saling timpa. Hantaman kepala dan sepatu terus beradu sembarangan selama musiknya menyala. Bahkan ketika berhenti pun tidak lantas mereda. Masih saja ada yang coba mendaki pundak-pundak punggung yang terbuka, mereka tengah bersenang-senang tanpa belas kasihan. Dan itu kasar, juga lapar setengah sadar. Liar, mungkin itu kata yang paling tepat.
Ah, saya suka itu. Giring sekalian saja termosnya ke depan. Acuhkan teguran pelayan. Ini saatnya beradu badan, cairkan pekatnya anggur menjadi keringat.
Malam itu empat kawanan Kuda tampak benar berbahagia. Ratusan tetamunya dilayani dengan menghadirkan sejumlah konsentrasi kekacauan. Satu Aku Sejuta Kalian, kata mereka, dan kerumunan itu membentuk pusara di atas kepala-kepala yang tertendang di 365 Eco Bar. Memang, instrumennya pun ikut kacau. Tapi tidak begitu buruk, dan juga tidak terlalu penting. Lagipula siapa yang peduli? Selama mereka tidak pingsan, masih bisa bermain dan ingat kalau harus pulang ke Bogor setelah ini, semuanya akan baik-baik saja.
Terutama penyanyinya yang banyak celoteh, humornya terlalu punk untuk harga bir Eco Bar. Juga pemain gitarnya yang kalem-kalem tenggelam di pojokan, mungkin mabuk jamu. Saya sendiri mengambil posisi menyerong searah Tionghoa ceking yang sedang sibuk menyelesaikan solo drum – sederhana saja tapi dia terpeleset di ketukan terakhir. Bukan masalah besar, tentu saja. Di sampingnya, pria paling jangkung di band itu sedang tertawa menyaksikan semua kejadian, melepas instrumennya demi secelah nafas usai merentetkan belasan nomor ofensif berbasis lugas, singkat, padat, cepat-berjebakan yang akan membuat penggemar Andre Hehanussa muntah-muntah.
Bagi sebagian banyak orang, mungkin yang terlalu pintar – mapan berpendidikan dan mengejar harta, musik seperti ini tidak ada gunanya. Apa yang bisa diharapkan dari tiga kunci yang digeber singkat dan seorang berandalan buta nada di depan mikrofon? Amatir, ya. Nihilis? Tak tahu juga, tapi tampaknya. Melawan? Jelas, karena itu yang paling penting. Sia-sia? Mungkin, tapi justru itu bagian menyenangkannya; menjadi busuk dan melawan tatanan.
Kemudian ditambah dengan, seni bertumbukan alami, lengkap sudah. Tidak ada yang lebih indah daripada itu. Tidak juga John Lydon, Malcolm Mclaren atau Ramone Bersaudara. Atau Superman Is Dead. Atau Slank yang terkutuk karena bersetubuh dengan pemerintah. Atau mereka golongan anarkis, atau siapapun yang coba kritis mengubah dunia, dan masih (tetap) kecewa. Persetan dunia. Persetan semuanya. Terima saja. Gulung saja.
Hmmm...
Cukup sudah menjadi serius, marah terus, dan muak juga lama-lama terlalu naif. Intinya, lakukan saja semua hal yang kita suka, itu dia, acuhkan orang lain dan luncurkan setiap kata yang muncul dari kepala ke tulisan ini sekarang juga. Kebebasan tidak pernah ada kecuali jika kita melakukannya. Being honest and unmerciful, Lester Bangs pernah mengatakan itu suatu kali.
Blank Generation. Kosong. Harapan cuma jeritan masa depan, sedangkan kita sekarat untuk sekadar melewati hari ini. Here Today, Gone Tomorrow, sebut Joey. Itu semangatnya, dan Kuda berhasil membentuknya dengan secercap agresi sembrono yang sempurna: proto punk Ron Asheton bergejolak lojot Jello Biafra yang disempal akhlak Richard Hell berdaya gedor 80s hardcore Germs, Minor Threat, Vatican Commandos, Dead Boys, Black Flag, Bad Brains, dan silakan sebut lagi energi lain dari era itu. Tidak sesakit G.G Allin, tapi sementah Dirty Rotten Imbeciles, busuk.
Meski rumor banal itu telah saya dengar sejak dua tahun silam, tapi baru inilah kali pertama akhirnya saya sempat datang ke pertunjukan mereka. Dan benar saja: benturan fisiknya ternyata gila, menjurus ke memar berluka jahitan. Dan sejujurnya pula, baru di malam ini jugalah saya pertama kalinya mendengar Kuda lebih dari dua lagu. Menyedihkan, ya memang.
Jadi malam itu memang benar-benar telah saya tunggu sepenuhnya. Kalian akan menemukan buahnya pada setiap cerita tentang mereka di sini, The Kuda, satu dari sedikit band lokal sekarang bahkan untuk kalangan independen yang saya suka.
Dan kemudian, iya... kacamata.
 Risiko yang diambil untuk dapat terus melihat jelas itu ternyata harus dibayar setimpal. Setelah sang penyanyi dengan cantik mengocehi harga bir dia segera memimpin bandnya menghentak nomor berikut; satu komposisi yang saya tidak tahu judulnya, tapi ingat seruan ‘tai!’ di sepanjangnya.
Risiko yang diambil untuk dapat terus melihat jelas itu ternyata harus dibayar setimpal. Setelah sang penyanyi dengan cantik mengocehi harga bir dia segera memimpin bandnya menghentak nomor berikut; satu komposisi yang saya tidak tahu judulnya, tapi ingat seruan ‘tai!’ di sepanjangnya.
Sontak mikrofon dikerubuti, dari depan, dari samping, juga dari mereka yang memanfaatkan momen ini untuk stage dive tiban meniban tidak karuan. Saya, yang turut bersemangat namun sedang tidak selera untuk ikut melompat coba mempertahankan diri dengan satu tangan menenteng termos anggur dan yang lainnya menggenggam bungkus nikotin, sementara satu batang yang terbakar terselip di bibir.
Nyaman, tapi justru di situlah letak kesalahannya. Terjepit di tengah arena kerusuhan dengan tangan berjejal benda jelas saja mengurangi konsentrasi pertahanan diri. Maka rasakanlah: ketika tubuh-tubuh di sekitar yang juga terjepit ikut roboh terterjang, bahkan sound monitor pun bergulingan acak, sebuah bokong yang baru saja selesai diarak tiba-tiba jatuh melabrak sisi kanan kepala saya.
Lengah, bajingan, kurang awas. Hantamannya melontarkan kacamata mencelat entah kemana. Tidak sakit, tapi buram. Langsung saja reflek membungkuk, geragapan meraba diantara kolong-kolong kaki yang gelap. Tidak pakai lama saya menemukan kacamata sialan itu teronggok tidak jauh dari pijakan. Kondisinya: keparat, terbelah dua.
Bangsatnya, itu adalah kecelakaan kedua dalam seminggu ini. Yang sebelumnya terjadi di depan panggung Seringai ketika seorang teman baik yang kala itu terjangkit emosi mabuk berlebihan mendorong muka saya hingga mengakibatkan hal serupa, kacamata patah. Dan sejak itu pula saya hanya merekatkannya dengan lem kayu.
Mungkin seharusnya pengalaman dijadikan pelajaran. Tapi sering kali itu juga tidak ada gunanya. Pun juga rela ketika mengalaminya di hadapan penampilan impresif The Kuda yang membuat torpedo saya menjulang tajam dalam sekejap, menyaksikan semua kegilaan yang diperbuat orang-orang ini. Tidak ada keharusan, melanggar aturan, purba bertebaran kata kasar – bebas berkehendak seperti apa saja yang mereka inginkan.
Itu esensinya.
Kemudian yang saya lakukan berikutnya adalah mengeluarkan empat puluh ribu rupiah untuk memberi hormat pada Satu Aku Sejuta Kalian, dan merancang pertemuan. Tiba-tiba penasaran dengan apa saja yang bersarang di kepala mereka, kehidupan seperti apa yang mereka jalani. Saya akan mendatangi Kuda ke kandangnya, entah kapan, tapi segera.
***
Dua minggu sesudah panggung Ecobar, ketika tengah menunggu kereta masuk menuju Gondangdia, ponsel saya bergetar. Sebuah pesan dari nomor asing muncul. Saya pikir omong kosong provider lagi, tapi rupanya pertanyaan memastikan.
“Gw jamur dr The Kuda. Hari ini jadi interview?”
Ya, tentu saja. Saya sedang menunggu gerbong menuju kota Anda tiba. Bogor. Turun saja di stasiun Cilebut, susul bunyi pesan berikutnya. Ok. Ketika menyimpan namanya di buku telepon mendadak saya ketawa dalam hati setelah mengetikkan: Jamur Kuda, seperti yang juga tertulis di sampul album. Nama macam apa itu? Jika nanti misalnya kesialan menimpa saya sampai seorang petugas – ACAB – lancang mengecek ponsel dan kemudian menemukan dua kata tadi, mungkin saja dia akan dikira seorang bandar, penadah tahi.
Waktu yang harus dihabiskan untuk berdiri melewati enam belas stasiun sebelum sampai di tujuan adalah sekitar satu setengah jam. Kemudian tiga puluh menit dilanjutkan dengan ojek dan berjalan kaki sebelum akhirnya saya duduk di sebelah Idam, gitaris Kuda yang tengah menyaksikan video konser U2 di laptopnya.
Itu mungkin pukul empat sore di wilayah Keradenan, Bogor, kandang Kuda yang sehari-harinya berfungsi sebagai kantor desain dan show room mobil. Asbak-asbak di atas mejanya dipenuhi puntungan abu rokok yang berantak berserakan. Sebuah suguhan kopi hitam, yang diseduhkan langsung oleh Adipati, sang penyanyinya datang tidak lama setelah kami saling bersalaman kenal. Lantas dia duduk di sebelah saya. 
“Lo kenapa dipanggil Jamur?” saya coba mengakhiri penasaran, melontarkan satu kalimat pemecah beku selain menyeruput cangkir kopi.
Jamur, yang sekarang berpotongan rambut pegawai negeri dan memapas klimis bulu wajahnya menjawab sambil tertawa lalu. “Dulu rambut gua begini,” tangannya memeragakan bentuk bulat di atas kepalanya. Saya menebaknya keriting seperti beringin, atau ya pentol jamur, apa lagi. Nama aslinya Aditya Sutiadi.
Saya sebenarnya kurang suka melakukan pekerjaan wawancara – terutama dengan yang bergerombol seperti ini, karena perbincangan mesti silang melintang. Tapi selalu juga harus. Dan akhirnya harus, karena waktu semakin bergulir terus. Sebagai latar, Idam memutar Otis Reeding tipis-tipis, melembutkan suasana anomali dikelilingi asap yang menyelimuti sekawanan Kuda pinggiran kota Bogor ini. Sebagai catatan, tidak ada yang tidak merokok di ruangan ini – seingat saya, ya, karena saya lupa Jamur merokok atau tidak.
Dan kami pun mulai.
“Tadinya kita sok mau bawain Pink Floyd,” sebut Idam, “sampai Guruh Gypsy aja kita kulik.”
Saya tertawa tidak percaya. Ternyata benar, tidak sampai tiga kali latihan mereka sudah frustrasi. Apalagi Adipati, seorang yang pernah hidup bertahun di jalanan sebagai ‘punk kentrung’, menenteng gitar kemana-mana untuk mengamen, selain juga ampuh dijadikan modus naik bus gratis.
“Kagak ngerti gua musik kayak gitu. Nggak nyampe skill-nya, daripada jadi gila,” cetus Adipati.
Itu terjadi di akhir 2010 ketika ide band ini pertama kali tercetus. Kuda sendiri diambil dari nama binatang yang sering dijadikan kata ganti makian ‘anjing’ oleh mereka, untuk kemudian ditambahkan ‘the’ di depannya supaya terdengar keren.
Adalah “Jabber” yang merubah seratus persen semua rencana psyche-prog ambisius Kuda menjadi hardcore punk nihil tanpa kompromi berdurasi gertakan 18 detik. Idam yang menulis riff dasar lagu itu terinspirasi dari “Nic Fit”-nya The Untouchables, yang akhirnya dimasukkan sebagai hidden track debut Satu Aku Sejuta Kalian.
Setelahnya, sejarah mengalir begitu saja. Tidak perlu banyak pikir; tinggal pegang alat lalu keluarkan semua yang ada di kepala saat itu juga. Percepat temponya, jangan diulang. Sedot lagi anggurnya, teriak. Potong basa basi yang tidak perlu, lalu tancap. Pula sangat produktif hingga menciptakan puluhan nomor singkat dalam waktu yang singkat pula.
“Mungkin karena cara mabuk gua kali, ya. Kebanyakan minum jadinya nge-punk,” kata Adipati lagi, “gua nggak main yang lain-lain; ganja, pil-pil gitu, najis! Coba kalau gua suka, bisa jadi kali psychedelic.” Tapi dia juga menambahkan di belakangnya, “Ok, kita mainin punk, nih, cuma jangan kayak yang udah-udah. Ya maksudnya yang monoton, yang begitu-begitu aja.”
 Dalam arti lain, Kuda tidak mau mudah tertebak, alias bermain seenak pusarnya saja. Komposisi yang sengaja dibuat aneh, eksentrik – kena tanggung – penuh ranjau. Hajar sekencangnya selama sepuluh detik lalu beres. Atau bisa dari anthemic tiba-tiba drop dan sekonyong-konyong selesai. Begitu, terserah Kuda saja.
Dalam arti lain, Kuda tidak mau mudah tertebak, alias bermain seenak pusarnya saja. Komposisi yang sengaja dibuat aneh, eksentrik – kena tanggung – penuh ranjau. Hajar sekencangnya selama sepuluh detik lalu beres. Atau bisa dari anthemic tiba-tiba drop dan sekonyong-konyong selesai. Begitu, terserah Kuda saja.
Pada masa itu mereka berlima – satu anggota lain, Nanu telah mengundurkan diri dua tahun lalu – adalah para pemuda, mahasiswa pengangguran yang niat tidak niat menjalani kehidupan kuliah sehingga main musik selalu berhasil menjadi pelarian andalan, bersama, seperti kata Ahong, target yang dipancangkan: merilis album sebanyak-banyaknya, tidak peduli laku atau disenangi orang-orang, yang penting main terus, genjot penulisan lagu dan banyak bergaul agar jangkauan makin luas.
Hasilnya, setelah sekarang tidak satupun dari mereka berhasil jadi sarjana, Kuda telah memfisikkan karyanya lebih banyak dari, mungkin jumlah semester yang pernah ditempuh para anggotanya di kampus. Lima tahun dengan sembilan rilisan; EP, kompilasi, split, full, itu usaha do-it-yourself yang mengesankan. Memperlihatkan integritas, meski tidak semuanya juga benar-benar dikerjakan sendiri... Ya, tapi tidak ada gunanya juga mendebatkan perkara-perkara seperti itu lagi sekarang, karena setiap hal membutuhkan jembatannya sendiri-sendiri, termasuk kalimat absurd barusan ini.
Menjadi punk rock adalah tentang berani terus berumur delapan belas dan tolak semua hal yang menyebalkan. Sepertinya mudah, ya sepertinya. Ingat, itu adalah sebuah jalan panjang menuju kemapanan. Kita mungkin tidak bisa bertahan terlalu lama. Mungkin. Tapi coba mari tanyakan Adipati.
“Hidup gua mah jauh dari kata mapan. Semua, keseluruhan. Dari cara bicara, gua jauh dari mapan. Iya, kan? Secara intelek gua juga jauh dari mapan,” bunyi logatnya polos, Sunda lugu yang kasar.
“Seperti apa menurut lo intelek atau cara berpikir yang mapan itu?” sambut saya.
“Mungkin yang akademis,” jawab Adipati. Di belakangnya Idam ikut selenting menyahuti, “yang pretensius.” Kemudian Adipati lagi, “Ngapain sih kayak beginian lo tanyain, ini kan hal-hal yang cuma dinaik-naikin supaya...” dia tidak menyelesaikan kalimatnya, “buat apa sih sebenernya? Bullshit, kalau kata gua sih. Itu bukan hal yang untuk didiskusikan atau dibicarakan, itu mah kayak musik, dirasa aja cukup.”
Adipati, dia tidak menuliskan nama aslinya ketika saya minta, lahir di Bogor tiga puluh tahun lalu. Sempat tinggal di Bekasi selama fase street punk-nya yang dihabiskan dengan mengamen dan sering turun ke jalan mengikuti aksi-aksi sosialis pembela kaum tani. Itu dilakukannya ketika masih tercatat sebagai mahasiswa Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan jurnalistik, sebelum akhirnya diberhentikan secara tidak hormat karena terlalu sering digelandang ke kantor polisi.
Belakangan dia jenuh dengan segala tindak tanduk aktivis. Dia sadar jika kenyataan akan selalu berakhir sama: tidak juga dapat merubah apa-apa. Protes sosial mentok tembok, turun ke jalan terik panas-panasan, sementara dia sendiri kesulitan bertahan dalam keseharian, bahkan untuk sekadar makan. Itu sama halnya seperti orang sekarat yang memperjuangkan orang sekarat lainnya. Tidak akan sehat.
“Anjing, gua ngedampingin sepuluh ribu petani dari Lampung, berjuang ini-itu, tapi gua sendiri kelaperan. Bangsat, kata gua mah. Mereka yang segitu banyak sok-sok gua perjuangin... anjing, mending gua nolong diri sendiri dululah baru orang lain.”
Sialan pahit, memang.
Tapi tuahnya, Adipati jadi banyak membaca di masa itu. Melahap buku-buku yang beredar di kalangan aktivis. Dan dari situlah timbul hasratnya untuk sering menulis. Membuat catatan-catatan di buku harian atau kertas pribadinya. Apa saja dicurahkan, baik itu sajak, larik, lagu, sekelebat pikiran, kutipan, bubuhan ataupun sekedar celoteh absurd pengantar mabuk.
Ketika saya penasaran apakah semua kertas pikirannya itu diarsipnya dengan baik, Adipati menyambarnya dengan sentakan, “Nenek sialan! Nenek sialan!” dia mengulanginya hingga tiga kali sampai harus berdiri dari kursinya. Semua orang yang ada di ruangan itu lantas tertawa, pun Adipati, sekarang dia sudah mampu menghadapinya dengan tertawa. Jelas saya bertanya musabab dibalik hardikan tersebut, dan siapa pula nenek yang diseret-seret barusan.
Setelah mendengar jawabannya, ternyata iya, benar nenek itu telah sangat berdosa. Kalau saya yang mengalaminya, mungkin hardikannya bisa lebih kasar bin sundal kebun binatang daripada sekadar kata sialan. Ya maaf, orang tua. Tapi itu akan sangat, sangat wajar. Dan saya langsung terbayang reaksi muntab Adipati yang pasti lebih garang pada saat itu dibanding yang baru saja diperagakannya.
“Nenek gua,” katanya. “Semua kertas coret-coretan gua itu pada dibakarin sama dia. Buku gua juga banyak, dua karung hangus semua. Tinggal sisa dua yang bisa diselamatin, itu juga halaman-halamannya beberapa udah gosong. Njing!”
Saya ikut bersimpati untuknya tapi juga tidak bisa menahan tawa bersama anak-anak lainnya – ini sejenis lelucon miris. Ahong yang kemudian menceritakan asal muasal peristiwa pembakaran tersebut.
Jadi, ketika akhirnya Adipati pindah lagi ke Bogor dia tinggal bersama neneknya. “Neneknya si Pati – Adipati – itu killer banget,” kata Ahong. “Kita sering pulang mabuk nginep di kamarnya. Berisik banget, kan pasti. Pasang musik. Kadang-kadang juga sering minum diem-diem di kamarnya. Berantakan emang. Suatu kali, mungkin karena udah keterlaluan dan keseringan,” dia tertawa, “neneknya ngamuk. Jadilah kayak gitu.”
Sejak itulah Pati minggat dari rumah. Tinggal di sebuah warung internet tempat biasa anak-anak nongkrong, sekaligus mencari makan di sana dengan menjabat sebagai penjaganya. Tapi tempat paling baik untuk dirinya memang berada di luar rumah, lagipula apa yang lebih menyenangkan daripada fasilitas sambungan internet gratis, di mana kita bisa menyedot kuota jendela dunia dengan sebebas-bebasnya?
Bagi kawanan Kuda insiden itu malah memberi keuntungan secara langsung. Paling tidak sekarang ada satu anggota yang rajin menjaga jembatan pergaulan, membuka korespondensi, mengunggah informasi dan karya. Sementara satu per satu lagu tercetak, mereka juga mulai berkeliling main di berbagai gig seantero Bogor dan sekitarnya.
 Beberapa karya awal mereka selain “Jabber” meliputi “Zonder Pardon”, “She Went To Trance”, “Electra Complex” serta satu lagu yang terinspirasi dari Ian Dury, “Sex, Alcohol & Ego”.
Beberapa karya awal mereka selain “Jabber” meliputi “Zonder Pardon”, “She Went To Trance”, “Electra Complex” serta satu lagu yang terinspirasi dari Ian Dury, “Sex, Alcohol & Ego”.
Gerbong pertama dari deret rilisan fisik Kuda pun segera dilepas dalam 300 kopi sembilan lagu EP Mistery Torpedo yang direkam secara singkat: live dan tanpa amplifier, semua todong langsung ke mixer. Proses mixing pun dilakukan sendiri, Ahong yang melakukannya di warnet dengan hanya menggunakan headset komputer. Dasar, punk!
“Apa yang menyenangkan dari sound busuk?” tanya saya.
“Ya, referensi,” kata Idam. “Maksudnya, 80s hardcore yang bener, ya yang kayak begitu.”
“Karena memang di situ fighting spirit-nya,” sambut Pati. “Bisa juga karena sound busuk emang ngewakilin (hidup kita). Jadi lebih dapet emosinya,” katanya lagi.
Yang keren, desain sampulnya yang dikerjakan oleh Idam diambil dari guntingan majalah-majalah lama, untuk kemudian satu per satu ditempel menjadi sebentuk kesenian amburadul, persis etos kemandirian punk itu sendiri.
Kemudian cerita bergulir terus – 300 kopi dengan nomor seri itu ludes – sampai sebuah kesempatan lain tiba ketika satu surat elektronik mendarat di kotak pesan anak-anak Kuda. Woto Wibowo pengirimnya, alias Wok The Rock, pimpinan gembong Yes No Wave Music yang menyatakan ketertarikannya untuk mengedarkan gratis Mistery Torpedo secara maya, yang ternyata membawa mereka kemana-mana.
Salah satu orang yang mengunduhnya adalah Jimi Multhazam. Tahu? Penyanyi The Upstairs, Morfem, drummer Be Quiet. Sekali dengar dia langsung jatuh cinta dan memburu seluruh rilisan Kuda setelahnya.
“Mereka sesuai selera remaja gue. Sejak denger di Yes No Wave gue langsung kesengsem. Dari ide riff gitar, sampling rekaman, drumming sampai bass line-nya gue suka. Cuma satu, teknik rekamannya terlalu sederhana. Ternyata mereka rekaman secara live, dan mixing sendiri di warnet. Anjing! Makin ngefans gue,” begitulah bunyi email yang dikirimkan Jimi ke saya.
Di tahun 2012 Mike Virus, vokalis street punk The Virus mengurasi Kuda untuk masuk kompilasi solidaritas Punk Aid: Aceh Calling yang diikuti oleh 72 band dari seluruh dunia. Yang disertakan adalah “Circle Crop”, versi awal dari “Hantu Laut” sebelum liriknya direka ulang dengan indonesia oleh Cholil Mahmud, penyanyi Efek Rumah Kaca.
“Terus bagaimana pendapat kalian tentang punk di Aceh yang diburu dan ditangkapi, bahkan sampai dibotakin seperti kriminil?”
“Ya sulitlah. Kita lihat kenyataan aja dengan kondisi yang ada di sana, syariah dan segala macam,” jawab Pati.
Sulit bagaimana maksudnya, saya yang tidak puas dengan jawaban singkat seperti itu pun mengatakan, “Keberadaan mereka menurut gua tepat di sana. Ketika kita direpresif oleh sistem, di sanalah seharusnya punk banyak berkembang biak dan melawannya.”
Pati tertawa. “Itu terlalu sulit buat gua untuk dibicarakan.”
Sial. “Kalau The Kuda sendiri, seperti apa cara melawan kalian sebagai punk?”
“Ya bisa dibilang dari musiknya, misalnya kita bikin album.”
“Tapi kalian emang peduli dengan isu-isu sosial?”
Pati tertawa. “Kita lebih fokus ngurusin urusan personal. Hidup kita aja masih jelimet, ya urus diri sendiri aja dulu.”
“Bisa dibilang nihilis?”
Suasana agak diam sejenak. “Bisa iya, bisa tidak,” sahut Idam. Sedangkan Pati menjawabnya begini, “Kalau buat gua pribadi untuk mikirin isu-isu global, buset, mikirin diri sendiri aja udah mati-matian, gimana gua ngurusin yang di sana. Kita mah nggak maksain sesuatu yang bukan kapasitas kita. Kita aja masih bergumul dengan keseharian kita yang kayak begini.”
***
Meskipun Bogor sering dijuluki kota sejuta angkot, kendaraan umum tidak beroperasi selama dua puluh empat jam di sana. Para supir sudah berhenti bekerja di atas pukul sepuluh malam. Bahkan ojek pun, kalau bukan di tengah kota akan sulit ditemukan. Itu jelas menyebalkan bagi tukang keluyuran malam yang hanya membawa tidak lain dari tubuhnya sendiri. Atau mereka para pekerja larut yang tidak memiliki fasilitas pribadi. Sedangkan taksi, terlalu malas rasanya meladeni argo tembak mereka pada jam segitu.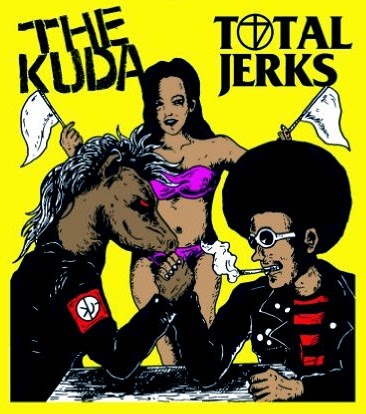
Lima hari sebelum kami bertemu, sekawanan kuda ini bisa jadi sedang mengutuki keadaan kampung halamannya sendiri itu ketika mereka harus pulang ke kandang dengan jalan kaki setelah menempuh kereta listrik paling malam dari Jakarta. Mereka baru saja melakukan wawancara dengan majalah musik paling terkenal di republik ini.
“Pas di Jakarta, sih keren abis dari Rolling Stun,” Pati melafalkan Stone dengan Sunda yang sangat sempurna, “pulangnya mah tetep, jalan kaki.”
Yang ternyata masih sering dilakukan, bahkan sambil menenteng alat selepas tampil. Salah satu jarak yang pernah ditempuh betis mereka adalah Cipete – Lebak Bulus, Jakarta. Dan sudah pasti, penyebab utama hal macam itu cuma satu: cekak biaya, tanpa daya.
“Makanya sekarang gini, Io... capeklah kita pulang manggung jalan kaki terus. Paling nggak, kita mah minta uang transportnya aja kalau main. Masa tega banget panitianya,” kata Pati. “Jadi enaklah di acara bisa minum. Nanti pas balik kan tinggal asyik duduk,” lanjutnya lagi.

Di tahun 2013 The Kuda dimitoskan. Dibuat fiktif oleh gerombolan Ruang Rupa sebagai band lokal bawah tanah yang aktif pada periode 70-80an, dipamerkan di The Asia-Pacific Triennial of Contemporary Art: Creating a Myth di Brisbane, Australia dengan digarami isu pengekangan kebebasan berekspresi yang menjerat di sepanjang pemerintahan Orde Baru.
Demi menguatkan alibi eksibisi, dikeluarkan juga sebuah album berisi enam lagu, yang sekalian saja dijadikan EP resmi kedua bertitel Duka Kuda. Hanya dicetak 100 kaset dengan nomor gubah ulang “No Fun”-nya The Stooges di dalamnya. Dan di sanalah mereka diberi pelajaran tentang menyanyikan Bahasa Indonesia oleh Cholil Mahmud sebagai penulis lirik “Hantu Laut” dan “Tumbila”.
Pati mengingat proses rekaman itu. Mengatakan ada banyak jembatan yang terputus antara gaya bernyanyinya dan aransemen melodi vokal tepat lirik arahan Cholil. “Rada kesel juga kali dia sama gua,” sebutnya. “Pas ngerjain itu gua bentrok melulu sama dia. Dia begini, gua begitu, jadi nggak pernah nyambung. Gua kan buta nada. Ya ngaku aja kalau nggak bisa nyanyi.”
Tahun itu pula The Kuda menulis lagu baru berjudul “Hey Jansen” untuk mendukung soundtrack Rocket Rain, film besutan sutradara Anggun Priambodo. Tidak jauh dari situ, EP ketiga kaset Spectabillies pun diterbitkan.
Saat ini ketika saya sedang mendengarkan cerita Idam tentang pencaplokan gitar Joy Divison di ‘Jansen’, sebuah tawaran panggung masuk melalui ponsel Pati. Tanpa menunggu Idam menyelesaikan bicaranya, Pati langsung menyeruak celah memberitakan kabar baik itu ke anak-anak. Tentu saja semua gembira, Idam sampai memotong kalimatnya seketika. Dia ingin mendengar lebih lanjut apa yang dikatakan Pati.
“Tapi mereka masih bingung masalah fee, katanya nih,” sebut penyanyi itu.
Berikutnya pembicaraan Batam ini diestafetkan saja kepada manajer mereka. Saya mendudukkan persoalan perbincangan pada debut Satu Aku Sejuta Kalian yang dirilis via Majemuk Records atas dorongan inisiatif seorang fans kelas berat bernama Jimi Multhazam.
“Kalau misalnya tidak ada Jimi, kapan kira-kira album ini akan rilis?” tanya saya.
Tidak ada jawaban pasti, malah saling berspekulasi dan tertawa. Mungkin masih tahun depan atau entah kapan. Awalnya, kata Pati, album ini dimaksudkan untuk menerbitkan materi-materi Kuda yang belum dirilis, yang sudah siap sebenarnya, tinggal mix sedikit lalu gandakan. Tapi sejak hard disk tempat lagu-lagu itu disimpan ternyata tengah berstatus gadai, maka hanya ada satu cara, yaitu rekam ulang. Lagipula tidak akan makan banyak biaya dan lebih segar. Beri mereka dua jam saja dan mereka akan memberi balik 20 lagu.
“Anjinggg ketawa-ketawa terus”, begitu Jimi mengingat hari-hari yang dilewatinya sebagai produser Kuda. Tugasnya adalah menjaga agar album ini tetap berada pada batas kenormalan manusianya. Rekamannya sendiri dilakukan di Streight Studio, Cipete, Jakarta Selatan dengan keterbatasan alat diakomodir dengan cekatan oleh Jimi yang meminjam kesana kemari.
“Gue menerjemahkan kemauan mereka dalam rekaman. Porsi gue cuma merekam ulang dengan system yang lebih baik. Dan mempertahankan kotornya sound mereka. Gue sampe bela-belain pinjam gitar Jazz Master Peter Damascus, Frontman amps Pandu Fuzztoni, Mustang si Batman GE sampai koleksi Cymbal Khemod Seringai. Untuk memaksimalkan hasil rekaman,” tulis email lainnya dari Jimi.
Beberapa nomor pilihan saya untuk album itu sendiri adalah, yang pertama “Lurid” karena judulnya dan seruan ‘We call... For you... To say... No!’. Lalu mars ‘holiday in the sun’ di “Lihatlah Lurus Ke Depan”. “Ilalang Hilang”. “Vita Brevis” karena Adipati adalah seorang pengarang absurd. “Hey Jansen” yang terdengar seperti angin ribut. Taik. Nomor delapan belas, lagu paling keren di album, “Tumbila”, yang digesek gitar Greg Ginn. “Upacara”, dan juga “Superstar” karena lirik biopiknya:
‘Oli pelumas
Karbonmonoksida
Kepul-kepul kehidupan
Antrian panjang... hahaha’,
yang ditulis oleh Jimi berdasarkan kehidupan Adipati sebagai montir vespa.
Sementara itu, baru saja semalam saya dengar cerita ini:
“The Kuda itu bukan punk. Punk itu nggak main di acara hipster. (Punk) Harusnya main di scene mereka sendiri,” kata seorang pentolan hardcore lokal senior ibukota – saya gemas ingin menyebut namanya tapi terus saja merasa segan – seperti diceritakan oleh seorang teman.
Saya ingat meresponnya dengan tertawa lebih dulu sebelum menimpali, “Maksudnya main di RRREC Fest atau Superbad?”
“Ya, mungkin maksudnya di acara-acara kayak gitu.”
 “Gila,” kata saya, “dasar kolot. Di jaman tukang mebel bisa jadi presiden masih aja mikir bego kayak gitu. Sempit banget. Harusnya orang-orang kayak gitu mati aja di era Soeharto kena putau supaya bangsa ini bisa berkembang. Scene atau bukan scene udah nggak penting lagi sekarang, menurut gua. Taik, hidup kebanyakan peraturan, mau ngelawan aja banyak banget aturannya. Being punk is being outsider. Fuck everyone else. Itu pasti karena bandnya udah nggak jalan lagi, kemakan jaman, makanya bisanya cuma ngoceh sekarang.”
“Gila,” kata saya, “dasar kolot. Di jaman tukang mebel bisa jadi presiden masih aja mikir bego kayak gitu. Sempit banget. Harusnya orang-orang kayak gitu mati aja di era Soeharto kena putau supaya bangsa ini bisa berkembang. Scene atau bukan scene udah nggak penting lagi sekarang, menurut gua. Taik, hidup kebanyakan peraturan, mau ngelawan aja banyak banget aturannya. Being punk is being outsider. Fuck everyone else. Itu pasti karena bandnya udah nggak jalan lagi, kemakan jaman, makanya bisanya cuma ngoceh sekarang.”
The Kuda sendiri sudah melepas batas-batas kekangan macam itu sejak pertama kali terbentuk. Tidak ada seragam. Juga keharusan. Menjadi punk adalah menjadi pendobrak aturan, kecuali mereka yang bergaris kanan... sial, coba bayangkan, betapa menyedihkannya menjadi punk tapi berhaluan kanan, kasihan, dan itu tidak akan habis jika dipikirkan atau didebatkan.
“Kita melawan hal-hal yang baku. Kayak album ini, musiknya kita bikin seenaknya. Orang lain mah bodo amat mau nganggep kayak apa,” sebut Pati.
“Kuda itu nyeleneh dan ngehe,” kata jamur.
“Kayak lo masuk ke kamar orang yang punya rasa seni aja,” cetus Pati lagi, “berantakan tapi enak dilihat. Kan beda sama kamar yang berantakan karena males.”
“Nggak tipikal, kita bikin musik yang orang nggak gampang nangkepnya, nggak ketebak,” itu Kuda menurut Idam.
Sedangkan Ahong yang dari tadi lebih banyak diam akhirnya angkat bicara setelah didesak-desak oleh sekawanannya. Dia memang agak pelit bicara hari itu.
“Kuda, ya Kuda aja.”
Itu saja? Singkat tapi saya anggap sudah jelas. Mereka tidak ingin menjadi apapun. Tak masalah juga jika mereka dianggap tidak atau kurang punk oleh orang lain. Bukan hal penting. Justru disitulah, The Kuda lebih punk dari pentolah hardcore tadi atau para pengguna anarki atau lem aibon sekalipun. Karena apa yang mereka jalani bukan gaya hidup menaati peraturan – punk rock 101 bla bla bla – tapi inilah kehidupan, kenyataan yang dijalankan sesuai kehendak mereka sendiri; menolak dan tidak nyaman menjadi normal. Persetan orang lain.
Menjadi punk adalah tentang menghidupinya. Bukan hanya, ‘saya marah’, ‘polisi bangsat’, ‘militer sialan’, ‘pemerintah anjing’, ‘tidak percaya agama’ dan ungkapan sumbu pendek seterusnya macam itu. Tapi ini tentang selalu menggenggam apa yang kita percayai dengan gairah, hati serta jiwa.
Atau tidak usah sekalian, toh pada akhirnya tidak ada gunanya juga. Anggap saja besok kiamat. Terserah. Satu mereka sejuta kalian. Selesai sudah.
Dan untuk penghabisan saya perlukan diri untuk mengutip bebait Pati di bawah ini:
‘Ketika kau tak tahu lagi apa yang mesti dilantangkan, kau berkata, “Aku lelah memberontak.” Lalu kau pejamkan matamu sejenak hingga berhalusinasi. Dan kau memakan semua kotoranmu. Makan wajahmu. Makan mulutmu. Makan hidungmu. Makan matamu. Makan otakmu. Makan tanganmu. Makan kakimu. Makan kupingmu. Makan dadamu. Makan penismu’.
Sial, dia sepenuhnya benar sebab saya tengah melakukannya sekarang.
<
Kredit Foto : Dokumen The Kuda &
















Comments (0)