
Parahyena: “Karena Hari Ini Folk Itu Seperti Berkiblat ke Amerika”
Parahyena berbicara panjang lebar tentang kenapa musik folk kita saat ini kurang mengeksplorasi budaya lokal
Sekitar setahun lalu saya menonton penampilan band bernama Parahyena di sebuah kafe di kawasan Progo, Bandung. Saya masih ingat dan terngiang-ngiang ketika mereka memainkan reff pada lagu “Cibaduyut”. Tentu saja, yang membuat saya tertarik adalah kesederhanaan musik mereka tentang kawasan yang dikenal sebagai penghasil sepatu ini. Padahal kalau ditilik-tilik, musik mereka justru jauh dari kata sederhana. Mereka memainkan suatu pola bernama “Trans-medium antara instrumen musik tradisi dengan musik pop-modern.
Berdiri di kampus seni ISBI Bandung pada tahun 2014, Parahyena yang terdiri dari Sendy (vokal dan guitalele), Radi Tajul Arifin (gitar dan vokal latar), Saiful Anwar (Contrabass), Cep Iman (biola), Fajar Aditya (Cajon), dan Fariz Alwan (Bangsing) mengaku sangat terinspirasi pada musisi lokal seperti Bing Slamet, R. Azmi, hingga budaya lokal seperti gamelan dan kecapi suling.
“Parahyena terbentuk karena kesengajaan. Maksudnya, karena memang awalnya bawa-bawain lagu-lagu cover. Pertama itu nggak tahu kalau Parahyena itu bawain musiknya bakal kayak gini. Namun kemudian aransemen itu memang dibawa ke ranah itu (etnis Sunda). Musikalnya Sunda emang sengaja digituin,” ujar Sendy (vokalis).
Saya menemui mereka di “markas” mereka di Kampus ISBI Bandung yang berada di daerah Buahbatu. Kebetulan masih banyak mahasiswa yang juga nongkrong. Mereka berbicara banyak tentang persoalan dunia kampus seni dan peran budaya lokal saat ini terutama pada konteks dunia musik.
Saya ingin menyoroti faktor kampus, apa kelebihan mendirikan sebuah band di kampus seni?
Kalau bedanya dari kemasan atau dari segi musikalitasnya, lebih luas. Referensi yang membuat suatu karya musik itu lebih luas dan masuk di wilayah seni. Kalau disebut kelebihan dan kekurangan sih pasti ada. Kalau kelebihan kebanyakan gini, misalnya tuh, duh malu euy, kalau disebut kelebihan sih kayak enggak ada (tertawa). Sama saja. Mungkin ada beberapa muatan lokal, walaupun di kampus sendiri sudah banyak yang mengangkat. Bahkan anak-anak metal juga sudah melakukannya untuk mengangkat budaya lokal. Nah, di ranah ini folk ini juga kan banyak juga, yang arahnya ke musik Irish, Scandinavian, atau Swedish, nah kami juga masih belum percaya diri apakah ini bisa disebut “folk” itu. Yah, kami bikin saja bentuknya seperti itu (memadukan musik Sunda –pen). Kalau kekurangannya, yang saya lihat misalkan di kampus seni seperti IKJ itu, scene-nya bisa lebih berkembang karena banyak dukungan baik dari media dan orang-orang dibelakangnya.
Atau bisa lebih bebas mabuk-mabukan (tertawa)?
Terlepas itu semua sih sewang-sewang (artinya, seorang-seorang). Nongkrong, bermusik atau nggak, mabuk sih jalan terus (tertawa).
Kalau kampus kesenian kan bisa lebih bebas yah?
Mungkin lebih tidak tekstual. Kadang ada kesulitan juga ketika ada pesan yang diusung ketika idealismenya sangat tinggi kalau di kampus seni. Kalau berbicara di kampus ini (ISBI Bandung), sedikit uniknya itu di wilayah tradisinya yang menjadi referensinya kuat. Kalau kami di sini kan memang tempatnya musik tradisi itu.
Kecenderungan yang saya lihat kan kalian satu tongkrongan di ISBI, kenapa yah kampus seni itu selalu berkiblat ke hal-hal yang lama atau klasik?
Kalau bisa dibilang karena kan kami juga di sini (Kampus ISBI), saya masuk kuliah di karawitan, kebanyakan kawan-kawan juga sama. Kan mereka memang harus menggali seni tradisi. Kalau berbicara wilayah skill, dia di kecapi atau suling otomatis jadi bisa. Nah, itu tuh harta kalau kata saya. Apalagi misalnya kalau membicarakan soal folk, kalau folk di kita kan kalau di Jawa Barat mengacunya ke kecapi suling atau tarawangsa. Kalau bicara kawasannya Jawa Barat, berarti yah gamelan. Karena hari ini folk itu seperti itu berkiblat ke Amerika, nah, gimana caranya budaya lokal ini juga kebawa. Yah udah dicampurkan saja.
Berarti apakah Parahyena itu antithesis dari folk barat Amerika itu tadi?
Kalau mengarah ke arah itu mungkin belom sih yah. Tapi kami sih berbuat saja dulu. Kalau pandangan saya mungkin seperti itu. Tapi tidak mengklaim kalau kami itu folk nusantara misalnya.
Pada satu sisi, kalian menggabungkan musik folk Barat, apakah latar belakang kampus itu yang membuat kalian bereksplorasi di wilayah musik tradisional?
Kalau disebut karena faktor kampus, iya, itu karena faktor kampus. Karena secara suara/bebunyian kalau lewat di kampus mendengarkan musik-musik tradisi ini. Jadi terbiasa mendengarkan suara gamelan, kecapi, suling. Dan itu jadi melekat di kepala.
Itu ada kesulitan nggak menggabungkan musik tradisional dengan folk/pop Barat?
Kalau kesulitan relatif. Kalau berbicara musik itu kan universal. Jangan ada kata yang dipatahkan dengan “selera”. Tapi kalau saya pribadi sih membuat musik yang mengombinasikan musik etnis dan pop Barat, kami sih senang-senang saja melakukannya. Enjoy saja.
Kalau di kampus seni yang saya perhatikan kayak di IKJ kan berkiblatnya ke retro, nah kalau di ISBI sendiri kan lebih kental budaya lokalnya. Ada nggak sih band pop yang mencampurkan musik tradisi seperti ini? Atau apakah ada tekanan dari pihak dalam yang menyebut bahwa kalian bid’ah dari kultur musik ISBI?
Ada sih beberapa. Tapi itu mah bukan berbicara pada konteks kreatif atau bermusiknya. Cuma itu lebih ke penilaian personal mahasiswa. Karena saya mahasiswa karawitan. Ini juga ada beberapa kubu. Kan di sini ada yang sangat konservatif terhadap tradisinya, ada yang lebih ke kreativitas dan inovasinya. Kalau kami pribadi, kan menggali apa yang terdekat dari kami saja. Yang tahu-tahu saja. Parahyena itu kan seperti itu. Ada di lagu pertama judulnya “Kembali”, melodinya itu gamelan Bali cuma diterapkan pada gitar dan biola.
Kalau musik tradisional kan ada degung, karawitan, kacapi suling, dan sebenarnya kan seperti lebih mudah akses untuk go internasional lewat term “world music” itu. Tapi kalau musik pop dengan campuran musik tradisi apakah bisa berbicara di luar negeri?
Yah, gimana yah, kalau secara musik mungkin bisa saja. Tapi terlepas dari kaminya juga sejauhmana usahanya. Pergerakannya seperti apa. Yah suatu saat mungkin bisa saja.
Kalian menyebut pola bermusik kalian “Trans-medium”. Sebuah pola perpindahan instrumen musik tradisi yang dipindahkan pada musik modern? Apakah ini hanya musik Sunda yang dipindahkan atau ada musik dari daerah lainnya?
Ada sih dari beberapa daerah lain juga. Tapi untuk album Ropea ini hanya beberapa. Lebih banyak unsur musik Sunda-nya. Tapi pada materi lain sih lebih variatif. Jadi nabung materi saja. Sekarang saja sudah ada materi untuk 3 (tiga) album ke depan.
Ada kesulitan tidak melakukan “Trans-medium” itu misalnya memindahkan pola kendang pada cajon atau hal lainnya?
Itu sih lebih latihan pribadi para personilnya. Kalau misalkan ini jadi “Dug” ini jadi “Tak”. Misalkan beatnya ngambil dari Cirebonan, Kendang Wayang, atau Jaipong. Terus, kecrek-nya apakah pakai apa, apa mau tambourine aja dipindahin ke gitar. Kayak biasa terdengarnya tapi nadanya adalah perpindahan medium tadi. Mungkin kalau berbicara kalau di wilayah teori, yang kesulitan itu di wilayah timbre. Karena timbre kendang itu kan membran, ada beberapa ornamen yang nggak dapat bunyinya di cajon itu. Ada keterbatasan bunyi karena memang beda.
Keterbatasan itu bagaimana mengakalinya?
Yah alternatif dan fleksibel saja. Jadi kalau berbicara pola kendang Jaipongan nggak melulu harus seperti itu. Jadi diambil intinya saja. Tapi bukan dari satu repertoire, tapi ambil dari satu motif. Yah, seperti ngambil “Mincid”-nya saja misalkan. Yang paling dirasakan enak saja.
Kalau melihat konteks kebudayaan kan, pada satu sisi geliat gelombang budaya “impor” terutama Korea, Jepang, Amerika, itu kan sedang banyak digemari oleh anak muda Indonesia. Nah, menurut kalian sendiri seperti apa peran budaya lokal dalam musik pop Indonesia kedepannya?
Kalau di tingkatan pelaku kayak musisi sih sebenarnya sudah banyak yang melakukannya. Musisi-musisi independen itu sudah banyak yang bereksplorasi melalui budaya lokal seperti Karinding Attack, Jasad, Forgotten, Kaluman, Tcukimay dengan kendang penca. Artinya sudah lama juga dieksplorasi. Pasti penikmatnya juga banyak.
Tapi apa yang saya perhatikan, eksplorasi budaya lokal atau menggunakan musik tradisional itu seperti hanya “tempelan” dan “gimmick” saja. Apakah kalian juga seperti itu?
Kami mencoba lebih ke mensenyawakan agar musik tradisi itu tidak sekedar tempelan. Kami mengaturnya biar porsinya pas. Jadi nggak “guguluyuran” yang tradisi enggak atau folk-pop juga enggak. Nah, kalau di tradisi yang kami anut sementara kan masih belajar juga nih, ketika bermain musik tradisi ada tingkatannya yaitu, “Wiraga”, “Wirahma”, dan “Wirasa”. Kalau memainkan musik tradisi sebatas tempelan masih pada tingkat “Wiraga”. Jadi kalau memainkan tradisi, menyatu lewat permainan jiwa dan niat. Kalau tingkat “Wirasa” tidak lagi main dengan otak tapi sudah dengan hati. Terasa soalnya yang main suling yang masih sekedar menghafal atau mengingat dengan yang memang sudah main dengan “rasa”. Karena seni itu wilayah estetika.
Kalau Parahyena sendiri pada level apa?
Kalau kami nggak merasa paling “Wirasa”, tapi kami cukup untuk berkarya dan bereksplorasi pada wilayah yang ini “Wirasa” versi kami. Belajar ngapalin enggak karena memang sudah pada hafal. Improvisasi juga bisa lebih berani.
Yang sekarang kan lagi tren musik folk, kemudian kalian muncul dengan musik folk dengan memadukan budaya lokal tadi. Perkembangan eksplorasi “folk” ke depan kalian itu bakal seperti apa karena banyak juga band-band yang menggunakan pola sama tapi mengalami stuck?
Kalau misalkan yang namanya band, stuck itu pasti ada. Tapi kami ingin mainnya nggak di situ saja. Kalau kami mainnya di musik Sunda, kan di musik Sunda sendiri masih banyak. Ada gamelan, angklung, dan masih banyak lagi. Itu tuh masih sangat memungkinkan untuk kami rekayasa.
Bisa diceritakan soal album Ropea, kenapa dinamakan Ropea? Apakah ini visi dan inovasi kalian sendiri untuk mengangkat budaya lokal dalam bentuk baru?
Ropea dalam bahasa Sunda kan artinya mengubah kembali. Kaitannya sama Parahyena, kan “Para” itu kawanan, “Hyena” itu anjing. Yang suka makan bangkai. Ini juga melihat apa yang sudah terlihat “basi”, maksudnya kan nah kami analogikan ada beberapa part musik tradisi yang kuno dan kami coba ambil elemennya untuk kami masukkan dan eksplorasi pada album ini. Ini tuh, pada tataran musik tradisi sendiri pola-pola yang kami pakai sudah nggak zaman. Makanya kami bawa ke ruang musik indie-pop/folk itu sendiri sehingga bisa menjadi benar-benar “baru”.
Kalian lebih nyaman pada ranah musik tradisional atau musik pop itu sendiri?
Kalau nyamannya sih kan bermain di luar kampus ini. Karena kampus ini mah lebih ke ruang prosesnya saja. Karena kan belum pernah latihan studio. Kami latihan di luar di area kampus saja.
Kalau lirik kalian apakah mengangkat juga budaya lokal?
Iya, lebih ke potensi daerah. Seperti pada lagu “Cibaduyut”, kan jadi ikon Kota Bandung. Kalau ngomongin sepatu sih Cibaduyut. Tapi sekarang kan ada Lazada (tertawa). Itu kaitannya dengan Ropea itu tadi. Nyambung. Mengangkat kembali hal-hal yang sudah basi. Jadi kalau pada lirik memang tidak terlalu banyak menawarkan. Maksudnya hanya semacam penulisan-penulisan cara pandang anak-anak gimana. Bahkan percintaan juga ada.
Nasib budaya lokal di tengah hegemoni budaya asing apakah dengan pendekatan musik dapat menjadi strategi yang efektif untuk mengangkat kembali budaya lokal?
Bisa, tapi nggak hanya musik sendiri. Harus semua berbarengan antara sastranya, teaternya, animasinya, dan filmnya. Karena sebenarnya yang lebih penting lagi apa yang tertulis seperti buku. Tulisan mungkin juga punya potensi penting selain lisan.
***
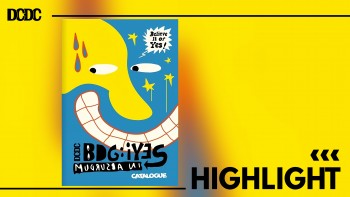














Comments (0)