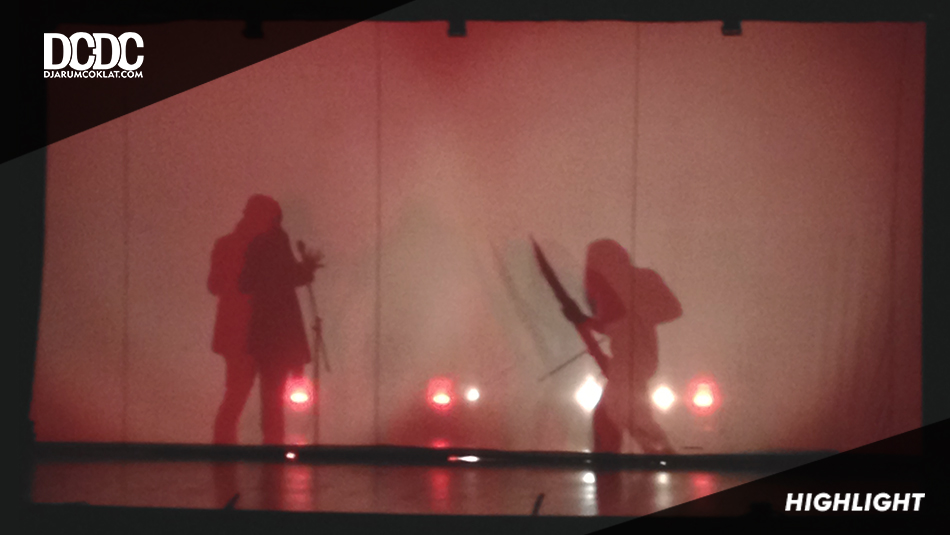
Konser Senyawa: Menemukan Otentisitas Musik Eksperimental
Konser tunggal perdana band eksperimental asal Yogyakarta Senyawa yang mampu menghadirkan derau yang intens dan primal hampir sepanjang tiga jam lebih
Kalau saja Dunia Barat sana tidak mengalami Renaisans, mungkin saja musik tidak akan mampu bereksplorasi sedemikian jauh. Musik kemudian merayakan pergeseran pusat dunia di mana manusia dan segala rasionalitasnya (antroposentrisme) menjadi titik tolak peradaban dan menggeser teosentrisme. Sosiolog Max Weber menuturkan bahwa rasionalitas itu membuat musik memungkinkan pada beragam eksplorasi material, teknikal, sosial, hingga psikologis. Alih-alih untuk aspek keilahian, musik kini lebih ditonjolkan pada “individualitas”. Akhirnya kemudian yang lebih ditonjolkan pada musik-musik setelah masa Renaisans ini kepada eksplorasi dan penemuan-penemuan baru (new discoveries).

Saya pernah menonton interview mereka dan mereka sendiri menolak ketika banyak yang mengaitkan musik Senyawa pada ranah musik etnik, musik tradisi, atau lebih menggelikan lagi, world music – yang mungkin kita masih cukup galau dengan definisi “world music” itu sendiri. Kalau Anda menyimak musik Senyawa, mungkin sekat-sekat itu sendiri menjadi tidak penting. Senyawa hadir melalui instrumen swadaya yang mereka rakit dan rancang sendiri menggunakan medium-medium “lokal” seperti bambu, alat bajak sawah, hingga spatula. Mereka yang selalu mengidentikkan Senyawa dengan musik etnik dan tradisi mungkin banyak yang “terjebak” dengan gaya vokal Rully Shabara yang banyak mengeksplorasi kekayaan tradisi oral di Nusantara.
Tak aneh dari segala eksplorasi itu, apalagi mendengar mereka telah malang melintang menjajal panggung dan festival di luar negeri, Senyawa akhirnya kembali “pulang” dan bersiap menggelar konser tunggal perdana mereka. Ekspekstasi kita bisa jadi cukup tinggi. Apalagi sebelumnya mereka biasa tampil pada panggung yang relatif kecil, baur dengan penonton, tapi menyajikan keintiman yang mampu membuat penonton terkesima. Ingatan yang sama ketika saya pertama kali menonton Senyawa beberapa tahun lalu ketika membuka tur Malaikat dan Singa di sebuah ruang alternatif kecil di Bandung.
Kali ini mereka tampil berbeda dan boleh dikatakan ini panggung yang layak untuk band sekelas Senyawa. Konser diselenggarakan di sebuah gedung bersejarah dengan tata visual yang mumpuni. Bahkan Rully Shabara berujar tentang bulan Desember yang seolah menjadi spesial bagi Senyawa. Saya tidak tahu kebetulan atau tidak pemilihan Desember menjadi bulan mereka menggelar konser tunggal perdana yang bertajuk “Tanah + Air” yang digelar pada 22 Desember 2016 lalu di Gedung Kesenian Jakarta. Desember selalu menjadi bulan spesial bagi Senyawa, setidaknya seperti yang diutarakan oleh Rully Shabara, bahwa Desember selalu jadi ajang Senyawa tampil di hadapan pecinta musik lokal – karena mungkin beberapa tahun terakhir mereka sering menjadi headliner festival di luar negeri.
Hanya ada layar putih yang ada di atas panggung dan menampilkan dua bayangan pria – hal itu mengingatkan saya dengan metode penampilan Sigur Ros. Seorang pria tampak dengan selongsong bambu mampu menghasilkan derau yang luar biasa menakjubkan. Wukir Suryadi, sang kreator dari instrumen musik Senyawa ini, mampu mempermainkan bambu yang diberi nama Bambuwukir ini sangat intens. Derau-derau itu bersahutan melalui hentakan ritmis, petikan, hingga gesekan. Bambuwukir seperti sahut menyahut membentuk komposisi drone yang sesekali berat namun bisa juga menjadi ringan melalui petikannya. Namun, kemampuan Bambuwukir itu mampu menjadi pola ritmis yang terus agresif dan menghentak tanpa henti menghadirkan suara-suara primal.
Bayangan pria lainnya lebih banyak menunjukkan kualitas vokal solid. Dia melafalkan dan mengeksplorasi tradisi-tradisi oral yang memang tumbuh subur di negeri ini. Kemampuan vokalnya bagi saya sih sudah cukup luar biasa dari olahan pitch hingga oktaf yang mampu terkontrol baik. Dia mampu menjelajahi beragam warna frekuensi suara dan teknik murni. Hal yang sama dilakukannya dalam band Rully selain Senyawa, Zoo, yang juga mampu menjelajahi ragam vokal yang kuat. Dia terdengar seperti meracau, berteriak, bernyanyi, atau berdendang dan semua terlihat solid dan tak terdengar kedodoran sama sekali. Rasanya hanya Rully yang mampu mengeluarkan teknik vokal seperti ini di Indonesia.
Pada saat konser berlangsung, cukup lama penonton tidak dibiarkan untuk melihat “sosok asli” dari Senyawa ini. Mereka hanya dibiarkan melihat sekedar bayangan dari para personil Senyawa seraya disuguhi kemampuan visual yang sangat apik. Seniman visual Andreas Siagian mampu menghadirkan olahan yang sangat kreatif dengan tampilan visual video yang terlihat bermain-main dengan sosok bayangan yang sesekali tampak membesar bak raksasa, atau mengecil bak kurcaci, atau juga bisa menampilkan efek visual dramatis yang mengikuti hentakan derau dari Wukir. Penonton terbius melalui sajian visual yang apik dan musik derau yang terus membentuk beragam interpretasi dalam benak kita.

Jika pada sesi pertama Wukir tampil bersama alat musik kesayangannya Bambuwukir, maka pada sesi berikutnya dia lebih banyak mengeksplorasi instrumen rakitan lainnya yaitu Garu, semacam alat bajak tradisional (sebelum era traktor) yang diubahnya menjadi instrumen musik eksperimental lengkap dengan dawainya. Kemudian juga ada Solet, yaitu suatu spatula tradisional Jawa berbahan kayu yang menjadi instrumen musik mirip gitar. Pada permainan Solet ini, misalnya, Wukir terus bermain-main seperti gitaris metal dengan alunan musik yang cukup “berat”.
Apa yang paling menarik dari musik, tentu ketika kita dikejutkan dengan hal-hal “baru”. Musik mampu menyingkap dunia manusia – dan segala rasionalitasnya - sehingga terus menerus mengeksplorasi berbagai harmoni, nada, irama, atau komposisi dengan segala kemungkinan tak terbatasnya. Menambah, mengurangi, membongkar, mengobrakabrik, dan memungkinkan segala elemen musik itu mampu melampaui berbagai definisi dan identitas. Ketika musisi/seniman kemudian terus menerus mengeksplorasi diri untuk menemukan sesuatu yang “otentik”, Konser Tanah + Air ini membuktikan bahwa Senyawa telah melampauinya.

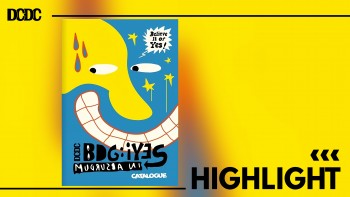














Comments (0)